Oleh: Abdul Rahman Lasading
KILASBANGGAI.COM – Razia buku selalu berulang dalam sejarah Indonesia, seperti sebuah drama yang diputar kembali dengan aktor berbeda, tetapi dengan naskah yang sama: rasa takut pada pengetahuan. Buku-buku dicurigai hanya karena labelnya—“kiri”, “tengah”, atau “kanan”—padahal sebuah buku, apapun muatannya, sejatinya adalah alat belajar.
Ia adalah pintu untuk memahami bagaimana ide-ide lahir, berkembang, diperdebatkan, dan bahkan ditolak. Negara atau aparat yang menyita buku sering berargumen soal keamanan, bahaya ideologi, atau ketertiban sosial. Tetapi mari jujur: adakah masyarakat yang menjadi lebih dewasa dan kuat dengan melarang bacaan?
Atau justru sebaliknya, larangan itu hanya melahirkan kecurigaan, mengekalkan ketidaktahuan, dan memperlebar jurang antara negara dan warganya? Buku-buku kiri, yang bicara soal keadilan sosial dan perlawanan atas ketidakadilan; buku-buku kanan, yang mengusung tradisi, konservatisme, atau religiusitas; hingga buku-buku tengah, yang mencari titik kompromi dan jalan moderat—semuanya adalah bagian dari proses manusia mencari jawaban.
Michel Foucault (1972) pernah menulis, “Pengetahuan bukan hanya sekadar alat untuk memahami dunia, melainkan juga medan pertarungan kekuasaan.” Maka, ketika negara merazia buku, yang sesungguhnya dipertaruhkan bukan sekadar teks di atas kertas, tetapi kuasa siapa yang boleh dan tidak boleh berbicara.
Belajar politik tanpa membaca karya kiri ibarat memahami sejarah musik dengan menutup telinga pada gamelan. Begitu pula sebaliknya: menolak bacaan kanan sama dengan menyangkal setengah dari lanskap gagasan yang hidup di masyarakat. Pengetahuan adalah medan pertemuan ide. Justru dengan membaca dan menguji semua spektrum gagasan, kita bisa belajar memilah mana yang masih relevan, mana yang harus dikritisi, dan mana yang mesti ditinggalkan.
Razia buku menghentikan dialog itu, memutus rantai belajar, dan mengajarkan generasi muda bahwa ketakutan lebih kuat daripada akal sehat. Sejarah dunia penuh bukti bahwa razia buku tidak pernah benar-benar memadamkan ide. Buku-buku Marx pernah dilarang, tetapi gagasannya menyebar di berbagai belahan dunia. Begitu pula teks-teks keagamaan atau filsafat yang berabad-abad ditolak penguasa, justru hidup kembali di tangan pembaca yang mencari.
“Kata-kata memiliki sayap,” tulis Salman Rushdie (1990), “bahkan ketika buku dibakar, gagasannya terbang melampaui api.” Tidak semua gagasan layak diikuti, bahkan banyak yang berbahaya. Namun justru di situlah esensi belajar: membedakan, menguji, dan mengolah pikiran. Menutup akses pada bacaan hanya akan menjadikan masyarakat rapuh, mudah percaya pada gosip atau propaganda, karena tak pernah ditempa oleh perdebatan gagasan yang sebenarnya.
Kajian dari Amartya Sen (1999) dalam Development as Freedom menunjukkan bahwa kebebasan berpikir dan berekspresi bukan sekadar nilai moral, tetapi prasyarat bagi kemajuan ekonomi, sosial, dan politik. Masyarakat yang dibatasi bacaan cenderung stagnan, sementara yang membuka diri pada arus ide lebih adaptif dalam menghadapi perubahan. Buku kiri, tengah, dan kanan adalah cermin perjalanan manusia mencari makna hidup bersama.
Menyita buku berarti menolak bercermin. Dan masyarakat yang tak berani bercermin hanya akan berjalan dengan wajah yang tak dikenalnya sendiri. Kalau kita ingin bangsa yang kuat, bukannya menutup buku, yang harus dilakukan adalah membuka sebanyak mungkin, lalu mengajarkan warganya bagaimana membaca dengan kritis. Sebab kebebasan berpikir hanya tumbuh subur di tanah yang tak ditaburi ketakutan.
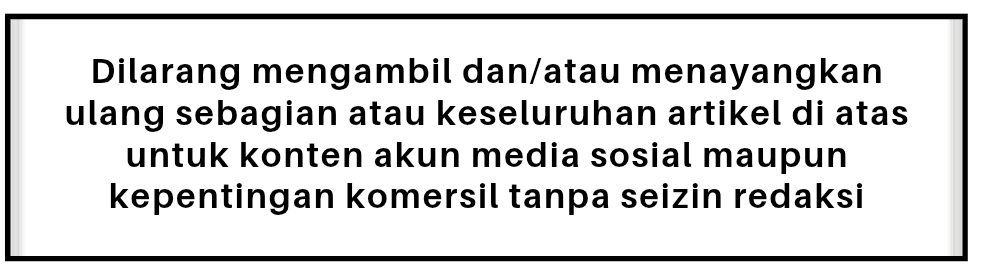
















Discussion about this post