Oleh: Supriadi Lawani
KILASBANGGAI.COM-Harga beras di pasar tradisional Kabupaten Banggai hingga kini masih bertahan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Beberapa waktu lalu, pemerintah daerah sempat mengeluarkan surat edaran yang melarang penjualan beras ke luar daerah, dengan alasan menjaga pasokan lokal dan menekan harga di pasar domestik. Namun kebijakan tersebut tidak berlangsung lama—ia dicabut setelah menuai kritik dan protes dari berbagai pihak.
Menurut sejumlah sumber yang enggan disebutkan namanya, surat edaran itu sejatinya hanya gimik politik, tidak memiliki efek substantif terhadap stabilitas harga beras di tingkat konsumen. Harga tetap tinggi, rantai distribusi tetap dikuasai aktor yang sama, dan struktur pasar tidak berubah. Di balik stagnasi kebijakan ini tersembunyi kenyataan yang lebih dalam: politik pangan di Banggai tak bisa dipisahkan dari struktur kekuasaan ekonomi di pedesaan, di mana para pemilik gilingan padi memainkan peran dominan.
Gilingan Padi Sebagai Struktur Kekuasaan Lokal
Sejauh pengamatan di lapangan, pemilik gilingan di Kabupaten Banggai bukan sekadar pengusaha penggilingan padi. Mereka adalah orang kaya desa, pemilik modal yang menguasai siklus hidup ekonomi petani kecil. Hubungan mereka dengan petani tidak berhenti pada transaksi ekonomi biasa, melainkan membentuk relasi patron-klien yang berlapis.
Para petani kecil kerap berhutang kepada pemilik gilingan untuk modal awal: uang tunai, pupuk, obat, hingga biaya tanam. Semua pinjaman itu dibayar saat panen melalui mekanisme potong hasil. Siklus ini terus berulang, menciptakan ketergantungan struktural. Dalam situasi seperti ini, pemilik gilingan tidak hanya menjadi pengendali ekonomi desa, tetapi juga penentu loyalitas politik. Ketika pemilu atau pilkada tiba, suara petani kecil praktis diarahkan oleh jaringan modal yang menopang keberlangsungan hidup mereka.
Henry Bernstein, dalam karya pentingnya Class Dynamics of Agrarian Change (2010), menjelaskan bahwa petani bukanlah kategori sosial yang homogen. Di dalam masyarakat agraris, selalu ada proses diferensiasi kelas—pemisahan antara mereka yang memiliki alat produksi (tanah, modal, dan sarana pascapanen) dan mereka yang bergantung pada tenaga kerja serta hutang untuk bertahan hidup. Diferensiasi inilah yang menjelaskan mengapa kebijakan pangan sering kali gagal: karena ia tidak menembus lapisan kekuasaan ekonomi-politik yang membentuk realitas di pedesaan.
Aliansi Politik dan Ekonomi di Tingkat Kabupaten
Elit kabupaten di Banggai tampaknya memahami struktur sosial ini dengan sangat baik. Mereka tahu bahwa untuk mengamankan dukungan politik di wilayah pedesaan, membangun hubungan patronase dengan pemilik gilingan jauh lebih efektif daripada sekadar mengandalkan mesin partai. Dalam berbagai kontestasi lokal, pemilik gilingan menjadi “broker politik” yang menghubungkan elit kabupaten dengan massa desa.
Beberapa informan bahkan menyebut bahwa beberapa pemilik gilingan besar di kecamatan Batui, Toili dan sekitarnya dilindungi oleh orang kuat di daerah, sebagai bentuk imbalan politik dari perhelatan pemilihan sebelumnya. Jika dugaan ini benar, maka kita sedang berhadapan dengan struktur politik pangan yang tertutup dan oligarkis—di mana kebijakan tidak lagi dirancang berdasarkan kebutuhan publik, melainkan untuk menjaga stabilitas relasi kekuasaan antara elit politik dan elit ekonomi desa.
Menuju Politik Pangan yang Demokratis dan Terukur
Dari sini dapat disimpulkan bahwa persoalan harga beras di atas HET bukan sekadar akibat fluktuasi pasar, tetapi hasil dari relasi produksi yang timpang di pedesaan. Petani kecil menjadi bagian dari sistem ekonomi yang tidak memungkinkan mereka menentukan harga hasil panennya sendiri, sementara pemilik gilingan dan aktor distribusi diuntungkan oleh struktur tersebut.
Maka, perbaikan harga beras tidak bisa hanya dilakukan melalui surat edaran atau larangan penjualan lintas daerah. Diperlukan reformasi struktural dalam tata kelola pangan—yang mencakup transparansi rantai distribusi, akses modal bagi petani kecil, dan penguatan kelembagaan ekonomi alternatif seperti koperasi tani.
Kebijakan pangan yang demokratis harus berangkat dari redistribusi kekuasaan ekonomi, bukan sekadar pengendalian administratif harga. Hanya dengan cara itu, negara (baca; Pemda) dapat benar-benar menjamin beras murah dan berkualitas bagi rakyat, sekaligus mengakhiri ketergantungan politik yang lahir dari relasi patronase di pedesaan.
Luwuk 31/10/2025
Penulis adalah petani pisang
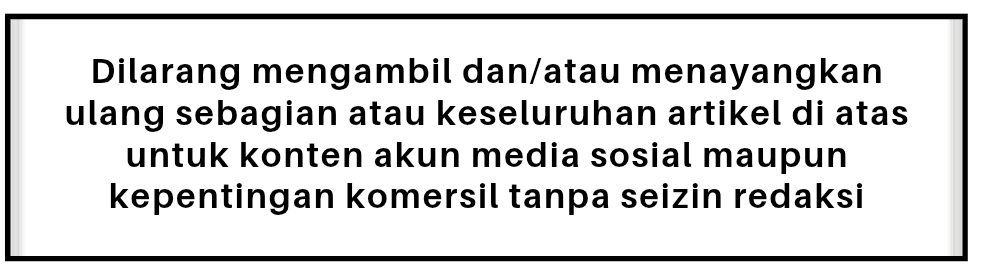
















Discussion about this post