Dandi Abidina (Rakyat biasa yang bercita-cita menjadi presiden)
KILASBANGGAI.COM – Politik pada dasarnya lahir dari cita-cita luhur yaitu memastikan kesejahteraan melalui organisasi negara. Namun sejarah politik selalu menunjukkan pola yang berulang idealisme yang baik dapat berubah menjadi mekanisme kontrol ketika kebijakan dirumuskan tanpa memahami konteks sosial yang menjadi fondasinya. PMK 81/2025 menjadi contoh segar bagaimana tujuan mulia pengelolaan fiskal dapat bergeser menjadi ancaman nyata bagi stabilitas sosial desa.
Pada tingkat makro, pemerintah pusat menghadapi tekanan fiskal yang serius defisit yang melebar, beban subsidi yang tak mengecil, serta belanja wajib yang terus meningkat. Dalam kondisi ini, pusat membutuhkan “rem darurat” untuk menjaga stabilitas APBN. Langkah yang dipilih adalah memotong pos anggaran yang dianggap paling fleksibel dan paling mudah dikendalikan Dana Desa non earmark. Secara teknokratis langkah ini dianggap rasional dana desa lebih mudah dikontrol daripada memotong anggaran kementerian yang penuh kepentingan politik, prosesnya cepat karena cukup lewat PMK dan efeknya langsung terasa pada fiskal nasional.
Namun di sinilah letak persoalan politiknya. Desa bukan sekadar bagian administratif negara, desa adalah ruang sosial dengan struktur budaya, ekonomi dan relasi kemasyarakatan yang kompleks. Ketika PMK diterbitkan secara mendadak, desa yang sebelumnya telah menjalani seluruh tahapan perencanaan formal RPJMDes, RKPDes, hingga APBDes mendapati bahwa pemerintah pusat justru merusak sistem yang dirancangnya sendiri. Perencanaan jangka panjang yang diwajibkan negara seketika kehilangan kepastian karena dana tahap II non earmark hilang begitu saja.
Dampak sosialnya sangat nyata. Tidak ada dana berarti tidak ada pembayaran untuk pekerjaan yang sudah berjalan. Gaji imam masjid, guru PAUD, guru ngaji, kader-kader pelayanan sosial dan seluruh unsur yang menopang kehidupan komunitas desa berhenti begitu saja. Ini bukan sekadar soal administrasi fiskal, tetapi soal keadilan sosial paling dasar. Orang-orang yang menggantikan fungsi negara di lapangan mendidik, membimbing, menjaga nilai, memelihara harmoni tidak mendapatkan haknya karena negara menarik diri melalui sebuah regulasi singkat.
Di beberapa wilayah, desa dipaksa memenuhi syarat teknokratis baru seperti koperasi Merah Putih. Ini secara konsep mungkin baik tetapi secara struktural tidak semua desa memiliki SDM, infrastruktur administrasi atau kapasitas teknis untuk memenuhi persyaratan tersebut dalam waktu singkat. Desa yang tertinggal bukan karena tidak layak, tetapi karena birokrasi yang terlalu rumit, akhirnya diposisikan seolah-olah tidak pantas menerima dana non earmark. Ini menambah ketimpangan dan mempersempit ruang otonomi desa.
Secara keadilan kebijakan, keputusan ini timpang. Pemerintah pusat ingin fiskalnya aman, tetapi bebannya dipindahkan ke desa. Yang merasa aman adalah pusat, tetapi yang menanggung dampak sosial adalah masyarakat desa. Di sini terlihat jelas problem struktural, desa adalah pihak paling lemah secara politik, sehingga menjadi sasaran yang paling mudah dipotong tanpa menimbulkan kegaduhan nasional. Jika anggaran kementerian dikurangi, akan ada resistensi politik. Jika alokasi provinsi dipangkas, konflik terbuka mungkin terjadi. Tetapi jika dana desa yang dipotong, suaranya terlokalisasi dan dianggap tidak mengganggu stabilitas politik nasional. Inilah praktik realpolitik yang memperlihatkan bahwa desa dipandang sebagai entitas yang bisa dikorbankan.
Dalam teori legitimasi politik modern, negara bertahan bukan hanya lewat hukum atau prosedur, tetapi melalui persepsi keadilan yang dirasakan masyarakat. Ketika imam, guru PAUD, kader sosial dan pekerja komunitas tidak mendapat gaji padahal pekerjaan mereka tetap berjalan, maka keretakan legitimasi negara dimulai dari titik sosial yang paling mendasar. Desa tidak lagi melihat kebijakan fiskal sebagai instrumen kesejahteraan, tetapi sebagai sumber ketidakadilan yang menekan mereka.
PMK 81/2025 adalah bukti bagaimana idealisme politik bisa bergeser menjadi ancaman ketika perumusan kebijakan tidak memahami realitas sosial. Kebijakan fiskal yang dimaksudkan untuk menjaga stabilitas nasional justru menciptakan instabilitas pada ruang sosial yang paling vital desa. Negara membutuhkan fiskal yang sehat, tetapi kesehatan itu tidak bisa dicapai dengan mengorbankan sendi-sendi kehidupan masyarakat lokal yang menjadi fondasi bangsa.
Jika politik pada awalnya diciptakan untuk melindungi masyarakat, maka keberadaan PMK ini menunjukkan adanya deviasi yang serius dari tujuan tersebut. Kembalinya kontrol anggaran ke pusat, hilangnya fleksibilitas desa, terputusnya penghasilan pekerja sosial, serta runtuhnya perencanaan desa menandai bahwa kebijakan ini bukan hanya cacat teknis, tetapi juga cacat etis.
Pemulihan keadilan hanya dapat dimulai dari satu langkah sederhana namun fundamental yaitu #CabutPMK81
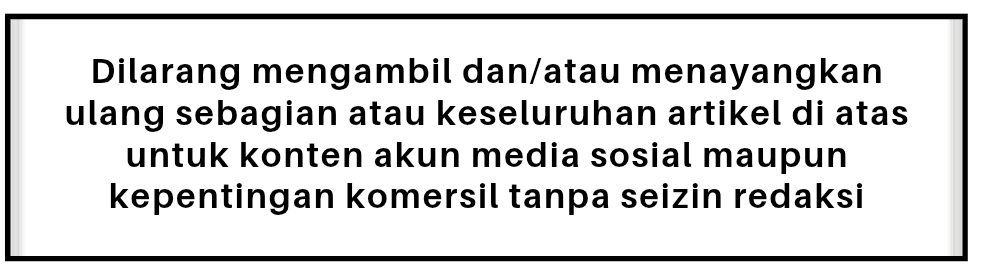
















Discussion about this post