KILASBANGGAI.COM – Dalam pengerjaan berbagai proyek di wilayah kabupaten Banggai, Sulawesi tengah, truk-truk pengangkut material tanah urug, tanah merah dan pasir silih berganti menurunkan muatannya. Material tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Namun, di balik aktivitas yang tampak normal tersebut, penulusuran media Kilasbanggai.com bahwa material galian C yang digunakan berasal dari penambangan yang di duga ilegal
Fenomena penggunaan bahan galian C atau Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) ilegal dalam pengerjaan proyek-proyek fisik yang menggunakan APBD telah menjadi praktik yang semakin meluas di berbagai daerah. Praktik ini menciptakan anomali yang menakjubkan sekaligus memprihatinkan.
Pengaturan terkait pengelolaan MBLB di Indonesia telah memiliki payung hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi dasar regulasi utama. Dalam UU tersebut, pertambangan MBLB masuk dalam kategori Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha pertambangan.
Setiap kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki IUP, IUPK, atau IPR. Ketentuan ini berlaku untuk semua jenis pertambangan, termasuk galian C yang sering dianggap sepele oleh masyarakat maupun aparatur pemerintah.
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara juga mengatur secara spesifik mengenai tata cara perizinan, kewajiban, dan larangan dalam kegiatan pertambangan. Tambahan lagi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur mekanisme pajak mineral bukan logam dan batuan.
MBLB sebagai salah satu sumber daya alam yang dikelola negara seharusnya memberikan kontribusi pada pendapatan negara melalui mekanisme pajak. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan termasuk dalam kategori Pajak Daerah yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022.
Tarif pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% dari nilai jual hasil penambangan. Dengan besaran tersebut, potensi penerimaan daerah dari sektor ini sangatlah besar. Namun faktanya, karena maraknya penambangan ilegal, potensi pendapatan ini hilang begitu saja.
Penggunaan MBLB ilegal membawa konsekuensi hukum yang serius, tidak hanya bagi penambang tapi juga bagi pengguna material tersebut. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020, pelaku penambangan ilegal dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar.
Yang sering diabaikan adalah bahwa hukum juga menjerat penadah atau pengguna hasil tambang ilegal.Termasuk kontraktor proyek pemerintah yang dengan sengaja menggunakan material dari sumber ilegal
Pasal 161 UU No. 3 Tahun 2020 menyebutkan bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan, atau mengolah hasil penambangan dari pemegang IUP, IUPK, atau IPR yang tidak memiliki izin usaha dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Ditengarai ada semacam pembiaran sistemik. Kontraktor dengan sengaja mencari material dari penambang ilegal karena harganya lebih murah, sementara diduga pengawas proyek menutup mata karena ada kepentingan tertentu.
Harga material yang lebih murah dari penambang ilegal menjadi insentif tersendiri bagi kontraktor untuk meningkatkan margin keuntungan.
Selain aspek legalitas dan potensi pendapatan yang hilang, penggunaan MBLB ilegal juga membawa dampak lingkungan yang serius. Penambangan ilegal umumnya dilakukan tanpa memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan reklamasi pasca tambang.
Penambangan MBLB ilegal sering menyebabkan kerusakan ekosistem sungai, longsor, dan bahkan tidak menutup kemungkinan menyebabkan banjir. Mereka tidak pernah melakukan reklamasi seperti yang diwajibkan bagi penambang legal.
Di beberapa kecamatan, kerusakan akibat penambangan ilegal telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Ironisnya, dana APBD yang seharusnya dapat digunakan untuk mengatasi dampak lingkungan tersebut justru dialokasikan untuk proyek-proyek yang menggunakan material ilegal menciptakan paradoks kebijakan yang sulit dipahami.
Menyelesaikan permasalahan ini membutuhkan pendekatan sistemik yang melibatkan berbagai aspek. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap proyek yang dibiayai APBD menggunakan material yang legal dan sah.
Perlu ada mekanisme verifikasi asal material dalam setiap proyek pemerintah. Kontraktor harus mampu membuktikan bahwa material yang mereka gunakan berasal dari tambang legal.
Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi kunci. Aparat penegak hukum harus berani menindak tidak hanya penambang ilegal, tetapi juga pengguna material ilegal, termasuk proyek-proyek pemerintah.
Pemberantasan praktik ini harus dimulai dari hulu ke hilir. Jangan hanya menindak penambang, tapi juga kontraktor dan oknum pemerintah yang terlibat. Di sisi lain, pemerintah perlu memberikan insentif bagi penambang untuk melegalkan usahanya, termasuk penyederhanaan proses perizinan dan pendampingan teknis.
Memutus rantai penggunaan MBLB ilegal dalam proyek APBD bukan sekadar upaya penegakan hukum, tetapi juga langkah penting untuk mengembalikan integritas pemerintah sebagai institusi yang patuh pada aturan yang dibuatnya sendiri. Tanpa hal tersebut, segala upaya penegakan hukum dan pembangunan berkelanjutan hanya akan menjadi retorika tanpa makna. (*)
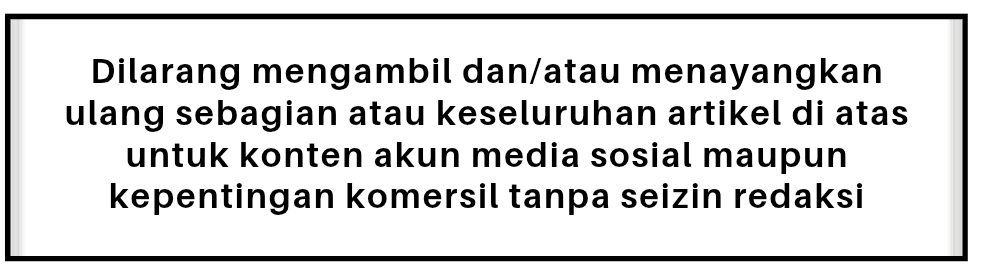














Discussion about this post