Oleh: Sandi Risno — Aktivis Lingkungan, Banggai.
KILASBANGGAI.COM – Ketika tanah hilang suara dan laut tak lagi memantul kehidupan, maka yang sedang terjadi bukan sekadar pembangunan, tetapi penjajahan ruang hidup. Pada Juli 2025, PT Bumi Persada Surya Pratama (BPSP) membabat habis sekitar 7,65 hektare hutan mangrove di pesisir Desa Siuna, Kabupaten Banggai, untuk pembangunan pelabuhan tambang dan area penumpukan bijih nikel. Apa yang dipertaruhkan bukan hanya ekosistem pesisir, melainkan keadilan ekologis dan moralitas kita sebagai manusia yang hidup berdampingan dengan alam.
Hutan mangrove di Siuna bukan sekadar vegetasi, melainkan rumah bagi ribuan organisme, penyaring alami, penyimpan karbon biru, dan pelindung pantai dari abrasi. Kehilangan ekosistem ini berarti kehilangan benteng perlindungan bagi nelayan dan masyarakat pesisir. Data dari lapangan menunjukkan keruhnya air laut, penurunan hasil tangkapan, dan kerentanan sosial-ekonomi yang meningkat. PT BPSP berdalih bahwa kawasan yang dibabat adalah APL (Areal Penggunaan Lain), dan mereka telah melakukan kompensasi berupa penanaman 10.000 bibit mangrove di Desa Tikupon. Namun pertanyaannya sederhana: apakah kerusakan di Siuna bisa ditebus dengan bibit di tempat lain? Jawabannya: tidak.
Dalam etika lingkungan, terdapat dua cara memandang alam: sebagai alat (instrumental value), atau sebagai sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri (intrinsic value). PT BPSP jelas menempatkan mangrove sebagai alat demi kepentingan industri, bukan sebagai bagian dari komunitas ekologis yang memiliki hak untuk hidup. Di sinilah relevansi pemikiran Aldo Leopold menjadi penting. Dalam Land Ethic-nya, Leopold menyatakan bahwa suatu tindakan hanya benar apabila ia menjaga integritas dan stabilitas komunitas biotik. Artinya, perusakan yang dilakukan PT BPSP tidak hanya salah secara ekologis, tapi juga secara moral.
Selain itu, kasus ini mencerminkan ketidakadilan lingkungan. Masyarakat pesisir sebagai pihak yang paling terdampak tidak dilibatkan secara berarti dalam pengambilan keputusan. Tidak ada mekanisme konsultasi yang terbuka, tidak ada transparansi informasi, dan tidak ada penghormatan terhadap prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC). Warga hanya tahu setelah pohon mangrove mulai tumbang dan perahu mereka makin sulit berlayar di perairan yang keruh. Ini adalah pelanggaran atas hak prosedural dan hak substantif mereka sebagai warga yang bergantung langsung pada alam.
Etika juga menuntut kita memikirkan generasi mendatang. Kerusakan mangrove hari ini adalah perampasan masa depan. Mangrove bukanlah ekosistem yang bisa tumbuh kembali dalam hitungan bulan. Ia membutuhkan waktu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun untuk kembali pada keseimbangan semula. Maka membiarkan pembabatan ini berlangsung adalah bentuk pengkhianatan terhadap prinsip keadilan antargenerasi.
Pemerintah daerah dan lembaga lingkungan hidup semestinya hadir sebagai penjaga. Namun yang terjadi adalah pembiaran. Kompensasi yang disetujui justru dilakukan di luar area terdampak. Apakah artinya kehancuran bisa dipindahkan dan dimaafkan hanya karena ada penanaman di tempat lain? Tidak. Kerusakan ekologis adalah kehilangan spesifik: lokasi, fungsi, komunitas, dan relasi ekologisnya tidak bisa digantikan dengan penanaman di desa tetangga.
Saya menyerukan agar pemerintah mewajibkan PT BPSP melakukan restorasi mangrove di lokasi terdampak. Tidak cukup dengan menanam bibit, tetapi dengan mengembalikan fungsi ekologis dan melibatkan masyarakat dalam seluruh prosesnya. Audit independen terhadap dokumen AMDAL juga harus dilakukan. Bila ditemukan pelanggaran atau manipulasi data, maka izinnya harus dicabut. Penegakan hukum tidak boleh lunak terhadap perusak lingkungan.
Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga harus diarahkan pada pemulihan ekonomi warga secara konkret, bukan simbolik. Pelatihan mata pencaharian alternatif, bantuan untuk nelayan, serta dukungan untuk usaha mikro berbasis ekowisata atau budidaya lestari adalah beberapa langkah nyata yang bisa dilakukan.
Yang lebih mendasar adalah perlunya pendidikan etika lingkungan dalam kurikulum lokal. Anak-anak Banggai harus diajarkan mencintai laut, mangrove, dan semua makhluk di sekitarnya, bukan hanya melalui angka ekonomi, tetapi melalui rasa hormat terhadap kehidupan.
Kasus di Siuna bukan hanya tentang pohon-pohon yang hilang. Ini tentang siapa yang punya kuasa, siapa yang harus diam, dan siapa yang berani bersuara. Dan saya memilih bersuara.
Kerusakan lingkungan bukan hanya soal kehilangan pohon atau ikan, tapi juga kehilangan nilai moral kita sebagai manusia. Jika pembangunan hari ini memaksa warga kehilangan tanah, laut, dan suara—maka kita sedang membangun di atas penderitaan. Maka, saya menyerukan kepada semua pihak:
Mari berpihak bukan pada yang berkuasa, tapi pada yang benar.
Mari berdiri bukan pada logika untung-rugi, tapi pada logika kehidupan.
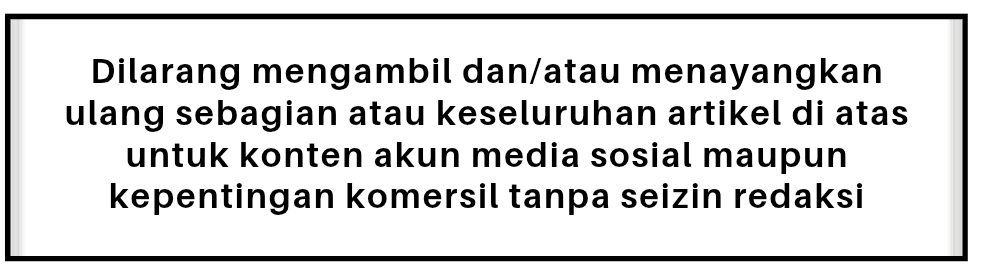














Discussion about this post